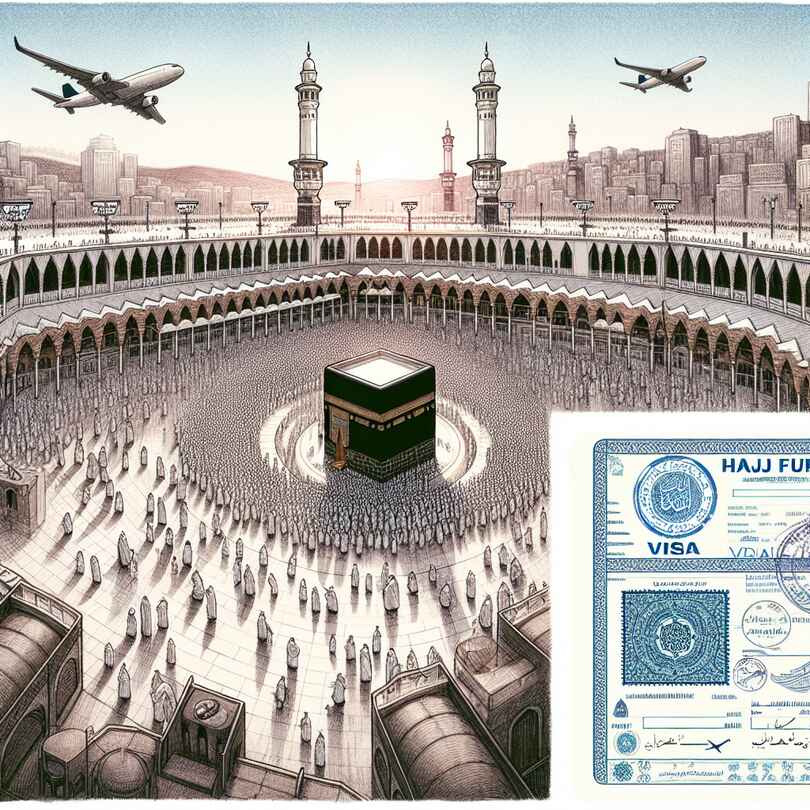Polemik Perbedaan Pendapat Seputar Hukum Haji Furoda/Mujamalah
Polemik Perbedaan Pendapat Seputar Hukum Haji Furoda/Mujamalah Dan Persepsi tentang Gharar dalam akad
Pendahuluan
Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang telah disepakati kewajibannya oleh seluruh ulama, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari syi’ar Islam.
Namun, perkembangan zaman, kondisi geopolitik, serta sistem birokrasi negara-negara modern telah melahirkan bentuk-bentuk teknis baru dalam pelaksanaan ibadah ini, seperti sistem kuota, visa reguler, visa mujamalah (Furoda), tasreh haji dll, hingga penyelenggaraan oleh pihak swasta yang bekerja sama dengan otoritas resmi.
Dalam konteks ini, muncul beragam pendapat—terkadang sangat tajam—terkait hukum keabsahan jalur haji non-reguler, khususnya haji Furoda/mujamalah, termasuk klaim bahwa ia adalah haram, karena bentuk muamalah yang mengandung gharar, bahkan sampai disebut “judi gaya baru.”
Lebih dari sekadar fatwa, isu ini menyentuh dua ranah penting:
- Kewajiban individu terhadap rukun Islam, khususnya dalam menghadapi konteks antrian panjang dan sistem birokrasi.
- Validitas akad jasa dalam sistem pemberangkatan haji Furoda, yang oleh sebagian berpendapat sebagai bentuk gharar yang dilarang.
Tulisan ini disusun berusaha untuk memberikan pandangan ilmiah yang sistematis, berbasis dalil, dan berimbang, dengan tujuan:
- Menjelaskan akar perbedaan pendapat (khilaf) seputar masalah ini.
- Mengurai adab dan kaidah ilmiah dalam menyikapi khilaf.
- Membedakan antara klaim gharar fāḥisy yang memang dilarang dalam syariat, dengan gharar yasīr yang dimaafkan dalam banyak akad.
- Menilai secara objektif: apakah benar haji Furoda merupakan akad muamalah yang batil karena mengandung gharar, atau justru merupakan ijarah yang sah secara fiqh?
Melalui pendekatan ini, diharapkan umat lebih objective dalam berpendapat, serta tidak terpaku pada satu pendapat, tanpa memahami dasar dari pendapat yang diambil atau disampaikan, serta tetap menjaga ukhuwah dan objektivitas ilmiah dalam perbedaan pendapat yang bersifat ijtihadiyah.
Sebab Terjadinya Khilaf (Perbedaan Pendapat) Dalam Islam.
Perbedaan pendapat (ikhtilāf) merupakan fenomena yang diakui keberadaannya dalam sejarah keilmuan Islam. Bahkan para sahabat Nabi ﷺ pun berbeda pendapat dalam banyak cabang hukum syariat, dan hal ini terus berlanjut di kalangan para tabi'in, imam madzhab, dan para mujtahid setelah mereka. Penyebabnya bukan karena tidak komitmen kepada kebenaran, melainkan karena perbedaan dalam:
- Memahami dalil (ikhtilaf mafhūm) serta penerapannya kepada objek permasalahan.
- Menilai kekuatan sanad (ikhtilaf fi al-tarjīḥ)
- Menentukan cakupan dalil (ām, khāṣṣ, mujmal, mubayyan)
- Kaidah-kaidah usul dan metode istinbāṭ yang digunakan
Imam Ibn Qudāmah رحمه الله menyatakan:
"وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْفُرُوعِ جَائِزٌ، وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي الزَّمَانِ الْفَاضِلِ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ."
"Para sahabat Rasulullah ﷺ berbeda pendapat dalam masalah cabang (furū‘), dan ini menunjukkan bahwa khilaf dalam furū‘ itu diperbolehkan. Maka jika mereka saja berbeda padahal berada di zaman yang mulia, maka generasi setelah mereka tentu lebih memungkinkan lagi untuk berbeda.” (Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Rawḍat al-Nāẓir wa Junnat al-Munāẓir fī Uṣūl al-Fiqh, tahqīq: Dr. ʿAbd al-Karīm ibn ʿAbd al-Raḥmān al-Namlah, Riyadh: Maktabat al-Rushd, cet. 3, 1419 H/1998 M, Jilid 1, hlm. 12)
Perbedaan ini harus dipahami dengan adab dan keilmuan, bukan dengan fanatisme tokoh, golongan atau menolak secara mutlak, apalagi sampai menyesatkan, merendahkan atau menuduh pihak lain memiliki tendensi karena sebagai pelaku muamalah haram tanpa kejelasan.
Adab Dalam Khilaf
Perbedaan pendapat di kalangan ulama bukanlah aib dalam Islam, namun menjadi keniscayaan karena keterbatasan manusia dalam memahami dalil, penerapan dalam objek, bahasa, dan konteks. Oleh karena itu, para ulama telah meletakkan adab-adab dalam menyikapi khilaf agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah umat.
Imam Sufyān ats-Tsaurī رحمه الله berkata:
"إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه"
"Jika engkau melihat seseorang melakukan suatu amalan yang diperselisihkan, sedangkan engkau berpendapat lain, maka janganlah engkau melarangnya.” (Ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa Faḍlih, Beirut: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, Jilid 2, hlm. 80)
Adab dalam khilaf di antaranya adalah:
- Tidak mengingkari dengan cara yang kasar terhadap masalah ijtihadiyah.
- Memahami bahwa perbedaan pendapat adalah kepastian dan bagian dari keluasan Islam.
- Tidak mencela, merendahkan atau menyesatkan pihak yang berbeda pandangan.
- Menjaga ukhuwah dan mengutamakan saling menasihati dengan hujjah, bukan emosi.
Ibnu Taymiyyah رحمه الله juga berkata:
"وَلاَ يُنكَر عَلَى مَنْ تَأْوَّلَ فِي مُسَائِلَ الاجْتِهَادِ"
"Tidak boleh mengingkari orang yang melakukan takwil (penafsiran) dalam masalah-masalah ijtihad.” (Majmūʿ al-Fatāwā, Jilid 20, hlm. 207)
Imam Ahmad ibn Hanbal رحمه الله juga berkata:
"رَأْيُ الأَوْزَاعِيِّ وَرَأْيُ مَالِكٍ وَرَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ كُلُّهُ رَأْيٌ وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا الحُجَّةُ فِي الآثَارِ"
“Pendapat al-Awzā‘ī, pendapat Mālik, dan pendapat Abū Ḥanīfah—semuanya adalah pendapat, dan bagiku semuanya sama. Yang menjadi hujjah hanyalah atsar (dalil syar‘i).” (Al-Khaṭīb al-Baghdādī, al-Jāmiʿ li Akhlāq al-Rāwī, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, cet. 1, 1401 H, Jilid 1, hlm. 207)
Imam al-Dhahabī رحمه الله juga menegaskan:
"مَا زَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ مُخْتَلِفِينَ، فَلاَ تَنْكَرْ عَلَى مُخْتَلِفٍ مَعَك فِي الْفُرُوعِ، وَعَظِّمِ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، وَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ"
“Ahli ilmu senantiasa berbeda pendapat. Maka janganlah engkau mengingkari orang yang berbeda pendapat denganmu dalam masalah cabang. Agungkanlah ilmu dan para pemiliknya, dan kembalikanlah ilmu kepada ahlinya.” (Siyar Aʿlām al-Nubalā’, Jilid 8, hlm. 432)
Dengan demikian, sikap seorang penuntut ilmu atau da’i dalam menghadapi khilaf bukanlah dengan memaksakan satu pendapat dan menyalahkan semua yang berbeda, tetapi bersikap adil dan ilmiah, serta hanya bersikeras dalam perkara yang telah jelas nash dan ijma‘nya.
Ssikap Taklid Buta
Taklid buta adalah sikap menerima pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya, bahkan ketika pendapat itu bertentangan dengan dalil yang sahih. Islam sebagai agama yang menekankan ilmu, tidak membenarkan seseorang bertaklid secara mutlak bahkan kepada ulama tanpa memahami hujjahnya, terutama dalam perkara penting yang berpengaruh terhadap hukum halal dan haram.
Allah Ta'ala berfirman:
"وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ"
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah', mereka menjawab: 'Tidak, kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.' Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk?" (QS. Al-Baqarah: 170)
Ayat ini mencela mereka yang bersikap taklid buta kepada nenek moyang atau tokoh mereka dalam hal yang bertentangan dengan wahyu Allah.
Imam Ibn al-Qayyim رحمه الله mengatakan:
"وقد ذم الله تعالى من ترك اتباع ما أنزل الله، إلى تقليد الآباء والأسلاف، وذلك من الجهل والضلال البين"
“Allah telah mencela orang yang meninggalkan mengikuti apa yang diturunkan-Nya, lalu malah bertaklid kepada nenek moyang dan leluhur. Itu adalah bentuk kebodohan dan kesesatan yang nyata.” (Ibn al-Qayyim, Iʿlām al-Muwaqqiʿīn, Jilid 1, hlm. 50)
Syekh al-Albānī رحمه الله juga berkata:
"التقليد الأعمى آفة خطيرة في طريق العلم والفهم، ومصدر كثير من الانحرافات في الدين"
“Taklid buta adalah penyakit berbahaya dalam jalan ilmu dan pemahaman, serta sumber dari banyak penyimpangan dalam agama.” (al-Albānī, al-Tasfiyah wa al-Tarbiyah, hlm. 26)
Imam Ibn Hazm رحمه الله berkata:
"من قلد عالماً فقد عصى الله تعالى ورسوله، وسيندم في الآخرة ندامة تتقطع لها القلوب"
“Barang siapa yang bertaklid kepada seorang alim (tanpa dalil), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kelak di akhirat ia akan menyesal dengan penyesalan yang meremukkan hati.” (al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Jilid 6, hlm. 118)
Imam Abu Hanifah رحمه الله berkata:
"حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي"
“Diharamkan atas siapa saja yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan pendapatku.” (Ibn ‘Abidin, Hāsyiyah Radd al-Muḥtār, Jilid 1, hlm. 63)
Imam Mālik رحمه الله juga berkata:
"إنما أنا بشر، أصيب وأخطئ، فانظروا في قولي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"
“Sesungguhnya aku hanyalah manusia, terkadang benar dan terkadang salah. Maka perhatikanlah pendapatku: segala sesuatu yang sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah maka ambillah, dan yang bertentangan dengannya maka tinggalkanlah.” (Ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa Faḍlih, Jilid 2, hlm. 32)
Oleh karena itu, meskipun seseorang bukan ahli ijtihad, ia wajib bertanya, memahami dan memilih pendapat yang didukung oleh dalil atau argument yang lebih kuat menurutnya. Allah Ta'ala berfirman:
"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"
"Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43)
Ayat ini menunjukkan bahwa bertanya adalah kewajiban orang awam, bukan untuk bertaklid buta, melainkan bertanya dengan niat mencari kebenaran dan hujjah yang sahih.
Imam al-Shatibi رحمه الله menegaskan:
"والتقليد الذي ذمه العلماء هو ما كان من غير معرفة بالدليل ولا تمييز بين الصواب والخطأ"
“Taklid yang dicela oleh para ulama adalah taklid yang dilakukan tanpa mengetahui dalil dan tanpa mampu membedakan antara yang benar dan salah.” (al-Muwāfaqāt, Jilid 4, hlm. 294)
Dengan demikian, mengikuti pendapat tokoh tertentu tanpa dalil, atau hanya mengikuti tanpa mau memahami dalil lebih mendalam, terutama dalam perkara besar seperti pengharaman ibadah atau pengguguran kewajiban, merupakan bentuk taklid buta yang diharamkan dalam agama, kecuali jika ada udzur seperti tidak memiliki kemampuan akal yang cukup, maka pada saat itu boleh ber taklid kepada tokoh yang dia percaya tanpa harus memahami dalil karena memang tidak mampu.
Setiap muslim, khususnya penuntut ilmu, harus mengecek dalil, memahaminya, memverifikasi hujjah, dan menghindari fanatisme pada tokoh tertentu.
Sikap Seorang Muslim Dalam Menghadapi Perbedaan Pendapat
Dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, seorang muslim dituntut untuk bersikap adil, ilmiah, dan berpegang teguh pada dalil, bukan fanatik terhadap tokoh atau kelompok tertentu. Khilaf adalah sesuatu yang lumrah terjadi di kalangan ulama sejak generasi pertama umat ini, bahkan di antara para sahabat Nabi ﷺ sekalipun. Namun, perbedaan pendapat itu tidak menyebabkan mereka saling mencela atau memusuhi.
Imam Malik رحمه الله pernah berkata:
"كلٌ يؤخذ من قوله ويُرد، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم"
“Setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini (Rasulullah ﷺ).” (Ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa Faḍlih, Jilid 2, hlm. 91)
Hal ini menunjukkan bahwa tolok ukur kebenaran bukanlah tokoh, ataupun ketenaran melainkan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.
Seorang muslim tidak boleh mudah mengklaim bahwa pendapatnya adalah satu-satunya yang benar tanpa memberikan ruang adanya ijtihad lain yang berlandaskan dalil. Dalam banyak kasus khilaf, kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak saja.
Imam Ahmad رحمه الله berkata:
"رأيي هذا رأي، وهو أحسن ما رأينا، فمن جاءنا برأي خير منه قبلناه"
“Pendapatku ini hanyalah pendapat. Itu adalah yang terbaik yang kami miliki. Jika ada yang datang dengan pendapat yang lebih baik darinya, maka kami akan menerimanya.” (al-Khallāl, al-Sunnah, Jilid 1, hlm. 126)
Sikap ini mencerminkan kerendahan hati dalam berilmu dan kesadaran bahwa kebenaran hakiki hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, ketika menghadapi fatwa yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama atau yang tergolong kontroversial, seorang muslim harus memeriksa hujjahnya secara seksama. Tidak serta-merta menolak, namun juga tidak langsung menerima hanya karena tokohnya terkenal atau dianggap pakar.
Imam al-Dzahabī رحمه الله berkata:
"من قال إن فلانًا معصوم، وقال قولًا مخالفًا للحديث الصحيح، فهذا ضالٌّ مبتدع"
“Barang siapa yang mengatakan bahwa si fulan itu maksum (tidak mungkin salah), lalu ia mengatakan sesuatu yang menyelisihi hadits sahih, maka orang itu sesat lagi ahli bid‘ah.” (Siyar A‘lām al-Nubalā’, Jilid 14, hlm. 376)
Dengan demikian, sikap seorang muslim yang benar dalam menghadapi khilaf adalah:
- Mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul-Nya (al-Qur'an dan Sunnah),
- Menghindari taklid buta dan fanatisme kepada individu atau mazhab tertentu,
- Bersikap adil dan berlapang dada kepada pihak yang berbeda pendapat,
- Mengutamakan ilmu, hujjah, dan dalil di atas popularitas tokoh atau tekanan sosial.
Jangan Mengatakan Halal Atau Haram Tanpa Dalil Yang Jelas
Salah satu prinsip utama dalam syariat Islam adalah tidak boleh menetapkan hukum halal atau haram tanpa dasar dari al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’ sahabat, atau qiyas yang sahih. Hal ini termasuk dalam hak prerogatif Allah dan Rasul-Nya.
Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu tanpa dalil, adalah bentuk kedustaan atas nama agama.
Allah Ta’ala berfirman:
"وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ"
"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta: 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS. An-Nahl: 116)
Imam ash-Shan‘ānī رحمه الله berkata:
"لا يحل لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله، أو إجماع الأمة، أو قياس صحيح"
“Tidak halal bagi siapapun untuk berkata: ini halal dan ini haram kecuali dengan dalil dari Kitab Allah, atau Sunnah Rasul-Nya, atau ijma‘ umat, atau qiyas yang sahih.” (Subul as-Salām, Jilid 2, hlm. 689)
Bahkan para imam mazhab yang mujtahid pun sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum. Mereka melarang pengikutnya untuk membabi buta mengikuti pendapat mereka jika bertentangan dengan nash syar‘i.
Imam Abu Hanifah رحمه الله berkata:
"إذا صح الحديث فهو مذهبي"
“Jika hadits itu sahih, maka itulah mazhabku.” (al-Zarkasyī, al-Baḥr al-Muḥīṭ, Jilid 6, hlm. 328)
Dengan demikian, menetapkan hukum tentang sesuatu adalah halal dan haram, atau mengklaim bahwa suatu ibadah wajib atau tidak wajib atau menjadi haram hanya karena mengikuti pendapat seorang tokoh tanpa memahami dalilnya, atau asumsi pribadi atau emosi atau karena pendekatan ekonomi, ataupun tendensi tanpa landasan dalil yang valid, merupakan tindakan yang sangat berbahaya dalam agama ini.
Adapun tokoh yang berpendapat dengan dalil-dalil yang dia yakini, maka ini adalah perkara ijtihadi dalam satu permasalahan, sehingga diberikan ruang toleransi dalam perbedaan pendapat.
Permasalahan Khilaf Seputar Haji, Furoda/Mujamalah Atau Semisalnya
Setelah memahami pentingnya sikap adil dalam menyikapi khilaf dan larangan menetapkan halal-haram tanpa dalil, maka kita masuk pada salah satu isu kontemporer yang sedang menjadi polemik: hukum haji furoda, termasuk di dalamnya haji mujamalah, serta pernyataan sebagian pihak bahwa haji tidak lagi wajib bagi warga negara Indonesia.
Permasalahan ini meliputi beberapa poin penting:
Hukum Haji dan Dalil Kewajibannya
Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang disepakati kewajibannya bagi yang memenuhi syarat istithā‘ah (kemampuan), dan merupakan ijmak ummat, ma’lumatun biddoruroh (perkara yang semuanya tahu) Allah Ta‘ala berfirman:
"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ"
"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Āli ‘Imrān: 97)
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
"بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ... وَحَجِّ الْبَيْتِ"
“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah... dan haji ke Baitullah.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Khilaf Mengenai Waktu Pelaksanaan Haji
Para ulama berbeda pendapat apakah haji wajib dilaksanakan segera (الفور) atau boleh ditunda (التراخي) setelah seseorang memiliki kemampuan (istithā‘ah):
Pendapat mayoritas ulama (jumhur): Haji wajib dilakukan segera setelah seseorang memiliki istithā‘ah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi‘iyyah, dan sebagian Hanabilah.
Dalil mereka adalah:
- Perintah dalam ayat dan hadits bersifat langsung tanpa ada indikasi bolehnya penundaan.
- Khawatir seseorang wafat sebelum menunaikannya sehingga mati dalam keadaan meninggalkan kewajiban.
Ibn Qudāmah al-Maqdisī رحمه الله berkata:
"وإذا استطاع الحج لزمه على الفور، فإن أخره أثم، في قول أكثر أهل العلم"
“Jika seseorang telah mampu berhaji, maka ia wajib melakukannya segera. Jika ia menundanya, maka ia berdosa menurut kebanyakan ulama.” (al-Mughnī, Jilid 3, hlm. 227)
Pendapat sebagian ulama Hanabilah dan lainnya: Haji boleh ditunda selama tidak ada kekhawatiran ia akan wafat atau lupa melaksanakannya.
Dalil mereka:
- Nabi ﷺ baru berhaji pada tahun ke-10 Hijriyah, padahal kewajiban haji turun sebelumnya.
- Tidak ada dalil eksplisit yang menyatakan bahwa pelaksanaan harus segera setelah istithā‘ah.
Fatwa Ulama Kontemporer:
Syaikh al-Albani رحمه الله berkata:
"من استطاع الحج فعليه أن يسارع قبل أن يُحال بينه وبين ذلك، فإنه لا يدري ما يعرض له"
“Barang siapa yang mampu berhaji maka hendaklah ia segera berangkat sebelum ada sesuatu yang menghalanginya, karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya.” (Hajjatun nabi, hlm. 16)
Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله mengatakan:
"الواجب على من استطاع السبيل أن يبادر بالحج ولا يجوز له التأخير بلا عذر، وإذا أخره فهو آثم عند جمهور أهل العلم"
“Wajib atas orang yang mampu untuk segera menunaikan haji dan tidak boleh menundanya tanpa uzur. Jika ia menundanya, maka ia berdosa menurut mayoritas ulama.” (Majmū‘ Fatāwā Ibn Bāz, Jilid 16, hlm. 376)
مَن قَدَرَ عَلَى الحَجِّ وَلَمْ يَحُجَّ الفَرِيضَةَ وَأَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى مُنْكَرًا عَظِيمًا وَمَعْصِيَةً كَبِيرَةً، فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ إِلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ وَالبِدَارُ بِالحَجِّ
“Barangsiapa mampu untuk pergi haji, namun tidak pergi haji yang wajib dan mengakhirkannya tanpa udzur (alasan yang dibenarkan syariat), maka dia telah berbuat kemungkaran yang dahsyat serta kemaksiatan yang besar. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dan segera menunaikan haji.”
(Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi‘ah, Syaikh Ibn Bāz)
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله berkata:
"من استطاع الحج ثم لم يحج حتى مات فهو آثم، وبعض العلماء يرى أن هذا من الكبائر"
“Barang siapa yang mampu berhaji lalu tidak berhaji hingga meninggal, maka ia berdosa. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini termasuk dosa besar.” (Fatāwā Nūr ‘ala ad-Darb, no. 1069)
Kapan Seseorang Boleh Menunda Haji? Penundaan hanya dibolehkan jika ada uzur syar‘i seperti:
- Masih menanggung hutang yang mendesak dan wajib dilunasi segera.
- Tidak adanya keamanan perjalanan.
- Keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan.
- Belum ada mahram bagi wanita (menurut sebagian pendapat).
Tanpa alasan tersebut, maka penundaan haji adalah maksiat, bahkan menurut sebagian ulama termasuk dosa besar, dan kewajiban tetap melekat hingga ia menunaikannya atau diwasiatkan agar dihajikan setelah wafat.
- Istithā‘ah: Definisi Klasik dan Aplikasi Kontemporer
- “Istithā‘ah” Menurut Ulama Salaf
Istithā‘ah secara bahasa berarti kemampuan. Secara istilah dalam fiqh, istithā‘ah adalah terpenuhinya syarat-syarat yang memungkinkan seseorang menunaikan ibadah haji secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan.
Ibn Qudāmah رحمه الله menyebutkan:
"الاستطاعة: الزاد والراحلة، بشرط أن يكون فاضلاً عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله"
“Istithā‘ah adalah (memiliki) bekal dan kendaraan, dengan syarat kelebihan dari kebutuhan pokoknya dan nafkah keluarganya.” (al-Mughnī, Jilid 3, hlm. 89)
Maksudnya dia memiliki bekal perjalanan selama haji, dan ada kendaraan yang bisa digunakan untuk mengantar, serta sudah mencukupi kebutuhan pokoknya dan nafkahnya kepada keluarga selama dia pergi haji.
Istithā‘ah pada Masa Kini
Konsep zaad (bekal) dan rahilah (kendaraan) pada masa lalu sangat literal: seseorang yang mampu membeli unta dan membawa bekal makanan untuk perjalanan pulang pergi. Namun dalam konteks masa kini, bentuk bekal dan kendaraan berubah menjadi:
- Biaya haji dan akomodasi,
- Transportasi modern (pesawat, bus, dll),
- Kesehatan dan keamanan pribadi,
- Kelayakan usia dan kesiapan fisik.
- Tambahannya adalah Kemampuan administratif: legalitas, visa, dan sistem kuota,
Dengan demikian, istithā‘ah masa kini tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga logistik dan kebijakan pemerintah.
Apakah Mendaftar Haji Termasuk Istithā‘ah?
Pertanyaan penting muncul:
Apakah cukup dengan mendaftar haji reguler maka kewajiban sudah gugur? Jawabannya perlu dirinci:
- Jika seseorang hanya mampu secara finansial untuk mendaftar haji reguler, dan itu satu-satunya pilihan yang tersedia baginya, maka ia sudah menjalankan kewajiban sesuai kadar kemampuannya.
- Namun jika seseorang memiliki kemampuan membayar wasilah yang lebih cepat apakah melalui haji plus atau furoda dan tidak ada uzur syar‘i untuk tidak memilihnya, maka wajib atasnya memilih jalur yang memungkinkan haji dilakukan lebih cepat.
Kaidah usul fiqh yang berlaku dalam hal ini adalah:
"مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ"
“Apa yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengannya, maka perkara itu hukumnya wajib.”
Jika pelaksanaan haji tidak bisa disempurnakan kecuali dengan akses visa yang hanya tersedia melalui jalur Furoda/mujamalah, maka mengakses jalur itu menjadi wajib jika memiliki kemampuan sesuai dengan kaedah, sebagaimana dijelaskan oleh:
Imam al-Āmidī dalam al-Ihkām:
"إذا تعين شيء طريقًا إلى فعل الواجب، وكان لا يمكن بدونه، صار ذلك الشيء واجبًا"
“Apabila suatu perkara menjadi satu-satunya jalan untuk melaksanakan kewajiban, dan tidak mungkin menunaikannya tanpa hal tersebut, maka perkara itu menjadi wajib.”
(al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, 1/129)
Imam al-Suyūṭī dalam al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir:
"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عند الجمهور، وهو القياس الجلي"
Apa yang tidak sempurna terlaksananya suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu wajib menurut jumhur ulama. Dan ini termasuk bentuk qiyās yang jelas (qiyās jallī).”
(al-Asybāh wa al-Naẓā’ir, hlm. 60)
Syarat dan Ketentuan Jalur Haji Saat Ini (di Indonesia)
- Haji kuota Reguler (G to G):
- Biaya rendah
- Antrian 20–50 tahun
- Melalui pendaftaran resmi di Kementerian Agama RI
- Visa Kuota Pemerintah
- Haji kuota Plus (PIHK) (G To G):
- Biaya lebih tinggi
- Antrian 5–7 tahun
- Melalui travel resmi berizin dan terakreditasi
- Visa Kuota Pemerintah
- Haji non kuota (G To B/ G To C) Furoda (Jalur Perorangan) /Mujamalah (Jalur perusahaan saudi, syarikah/instansi/kelembagaan):
- Biaya sangat tinggi
- Langsung berangkat tahun tersebut
- Visa perorangan / Syarikah(Perusahaan) dari pihak Saudi
- Legal tetapi bukan dari kuota pemerintah Indonesia
Apakah Haji Furoda Dapat Disebut di Luar Kewajaran karena Biayanya?
Sebagian da’I berpendapat bahwa haji furoda tidak termasuk dalam kategori wajib karena biaya yang sangat tinggi dianggap di luar kewajaran. Mereka menganalogikan dengan kasus seseorang yang bertayammum karena tidak menemukan air, lalu ia menemukan air yang dijual dengan harga yang sangat mahal, maka tidak wajib baginya membeli air tersebut untuk berwudhu atau mandi janabah.
Pendapat ini sering dikaitkan dengan pernyataan dalam kitab-kitab fiqh seperti:
"وإن لم يجد الماء إلا بثمن كثير فاضل عن ثمن مثله، لم يلزمه شراؤه"
“Jika seseorang tidak mendapatkan air kecuali dengan harga yang sangat mahal melebihi harga biasanya, maka tidak wajib atasnya membelinya.”
(al-Majmū‘ karya al-Nawawi, 2/219; al-Mughni karya Ibn Qudāmah, 1/167)
Namun, qiyas (analogi) ini perlu ditinjau secara mendalam karena ada perbedaan hakikat antara air sebagai syarat sah shalat dan visa haji sebagai jalan (wasilah) menuju kewajiban, (qiyas ma’al fariq), sehingga keduanya tidak bisa di qiyaskan.
Dan haji dikaitkan dengan istitha’ah, Dimana seseorang yang tidak memiliki kemampuan bahkan tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji.
Perbedaan Antara Pembelian Air dan Pembelian Layanan Haji
- Air adalah syarat sah ibadah, sedangkan visa adalah jalan administratif (wasilah) menuju pelaksanaan ibadah.
- Dalam tayammum, darurat air bersifat furu‘ (cabang hukum). Sementara dalam haji, visa atau jalur berangkat adalah wasilah (sarana) untuk menyempurnakan kewajiban yaitu rukun islam, dan hukumnya mengikuti tujuan.
- Kaidah usul menyebutkan:
"الوسائل لها أحكام المقاصد"
“Sarana itu hukumnya mengikuti tujuan.”
Maka, jika tidak bisa berhaji kecuali dengan jalur visa tertentu, maka jalur itu menjadi wajib—dan perlu di garis bawahi jika memiliki kemampuan.
- Biaya tinggi dalam haji furoda adalah biaya harga visa dan biaya jasa serta layanan yang sah secara syar‘I, dan hal itu adalah relative, maka tidak bisa di-qiyaskan mutlak dengan harga air yang ‘tidak lazim’ atau ‘zalim’, kecuali ada unsur gharar atau eksploitasi yang jelas.
Kesimpulan
- Jika harga furoda masih dalam batas kemampuan seseorang dan tidak sampai mengancam kebutuhan pokok atau menimbulkan bahaya ekonomi, maka tetap wajib.(Kembali kepada kaedah Istithoa’ah/kemampuan)
- Qiyas dengan air mahal dalam konteks tayammum tidak mutlak bisa dijadikan dalil untuk menggugurkan kewajiban haji.
- Maka yang dijadikan patokan adalah: mampukah seseorang secara syar‘i dan aktual untuk berhaji melalui jalur itu, dan tidak adakah cara lain yang memungkinkan secara waktu dan syar‘i? Jika iya, maka tetap wajib.
Polemik Haji Furoda dan Isu Gharar
Permasalahan gharar dalam akad haji furoda menjadi isu yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan, khususnya terkait keabsahan akad dalam fikih muamalah. Untuk itu, perlu dijelaskan secara sistematis berdasarkan pandangan para ulama.
Definisi dan Makna Gharar dalam Fikih
Gharar secara bahasa bermakna al-khathar (risiko tinggi) dan al-jahālah (ketidaktahuan). Dalam istilah fikih, gharar adalah akad yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa antara dua pihak.
Imam al-Nawawī رحمه الله berkata:
"الغرر ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما"
“Gharar adalah sesuatu yang berada antara dua kemungkinan, dimana yang lebih dominan adalah kemungkinan yang membahayakan.” (al-Majmūʿ, 9/286)
Ibn Qudāmah رحمه الله menjelaskan:
"الغرر: ما كان مجهول العاقبة، أو كانت عاقبته تؤول إلى مجهول"
“Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, atau akibatnya akan lebih mengarah kepada hal yang tidak diketahui (tidak jelas).” (al-Mughnī, 4/131)
Tidak Semua Gharar Terlarang.
Contoh Gharar yang Dilarang dan yang Dibolehkan
Gharar yang dilarang (Fahisy):
- Menjual ikan di air (HR. Muslim, no. 1513)
- Menjual burung yang terbang (Ibn Qudāmah, al-Mughnī, 4/132)
- Menjual janin yang masih dalam kandungan (al-Nawawī, al-Majmūʿ, 9/286)
Gharar yang diperbolehkan (yasir):
- Menjual rumah yang memiliki bagian tertutup seperti pondasi, tulangan besi dll (karena kebutuhan umum dan keumuman yang berlaku), (Lihat: al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 13/218)
- Syaikhul islam berkata:
ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رُخِّصَ فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضررًا من ضرر كونه غررًا، مثل بيع العقار جملة، وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المُرضع، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن."
“Dampak buruk dari gharar (ketidakjelasan dalam transaksi) itu lebih ringan daripada riba. Karena itu, gharar dibolehkan pada hal-hal yang dibutuhkan. Sebab, jika dilarang, justru bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada bahayanya gharar itu sendiri. Contohnya seperti jual beli rumah secara keseluruhan walaupun bagian dalam tembok atau pondasinya tidak diketahui, atau jual beli hewan yang sedang hamil atau menyusui, meskipun tidak diketahui jumlah janin atau banyaknya susu.” (Majmū‘ al-Fatāwā, 29/26)
Imam as-Sarakhsī berkata:
"الْغَرَرُ الَّذِي لَا يَخْلُو عَنْهُ التَّعَامُلُ يُتَسَامَحُ فِيهِ"
“Gharar yang tidak bisa dihindari dalam transaksi muamalah, maka dimaafkan.” (al-Mabsūṭ, 13/218)
Ukuran Gharar Dikatakan Fāḥisy
Para ulama memberikan batasan gharar fāḥisy (besar) yang diharamkan syariat, di antaranya:
Imam Ibn Qudāmah رحمه الله berkata:
"وكل بيع فيه غرر كثير، لا يدعو إليه ضرورة، فهو باطل، لما روى مسلم أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر"
“Setiap jual beli yang mengandung gharar besar, yang tidak darurat, maka hukumnya batil. Karena Nabi ﷺ melarang jual beli gharar.” (al-Mughnī, 4/131)
Imam al-Zarkasyī menjelaskan:
"إذا كان الغرر كثيراً غلب على العقد، فإن العقد باطل، وإذا كان يسيراً لا يمنع من تحقق المنفعة، كان صحيحاً"
“Jika gharar (ketidakpastian) jumlahnya banyak dan sangat mengganggu akad, maka akad itu batal. Namun, jika gharar hanya sedikit dan tidak menghalangi manfaat utama bagi salah satu pihak atau bagi objek akad, maka akad tersebut tetap sah.” (al-Manthūr fī al‑Qawāʿid, 2/334)
Ibn Taymiyyah رحمه الله berkata:
"والغرر إذا كان يسيراً لا يفسد به العقد باتفاق العلماء، وإنما يفسده الغرر الكثير الفاحش"
“Gharar yang ringan tidak membatalkan akad menurut ijmaʿ ulama. Yang membatalkan adalah gharar yang besar dan nyata.” (Majmūʿ al-Fatāwā, 29/23)
Kesimpulan: Gharar fāḥisy ditandai dengan:
- Ketidakpastian yang mencakup objek utama akad (maʿqūd ʿalayh),
- Potensi kerugian besar,
- Hilangnya hak pihak tertentu akibat ketidaktahuan,
- Gharar menyelimuti pokok akad, bukan sekadar wasilah atau detail kecil.
Perbedaan Gharar dalam Akad Jual Beli Barang dan Jasa
Perbedaan antara gharar dalam jual beli barang dan jasa menjadi poin penting dalam memahami akad-akad kontemporer seperti paket haji atau jasa travel.
Imam al-Qarāfī رحمه الله menegaskan perbedaan antara keduanya:
"الغرر في الأعيان أغلظ من الغرر في المنافع، لأن الأعيان مقصودة لذاتها، بخلاف المنافع"
"Gharar dalam barang lebih berat daripada gharar dalam manfaat, karena barang dimaksudkan secara zatnya, berbeda dengan manfaat." (al-Furūq, 1/157)
Al-Suyūṭī رحمه الله juga menegaskan kaidah ini dalam al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir:
"الغرر المفسد هو ما كان فاحشًا في المعقود عليه، وأما في المنفعة فإن الشريعة تتسامح به"
"Gharar yang merusak akad adalah gharar yang besar pada objek akad, adapun pada manfaat maka syariat memberi toleransi." (al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir, hlm. 151)
Imam al-Subkī juga menyebutkan prinsip serupa:
"العقد إذا وقع على معدوم محقق الوقوع جاز، كاستئجار الحجام والدلال والمزين، وكذلك الجراح، مع أن محل الإجارة معدوم، لكنه متوقع الحصول غالبًا"
"Akad atas sesuatu yang belum ada namun sangat mungkin terjadi adalah sah, seperti menyewa tukang bekam, makelar, penata rambut, dan juga dokter bedah. Meskipun objek jasa itu belum wujud, namun pada umumnya sangat mungkin terjadi." (al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir, al-Subkī, 1/61)
Imam al-Kāsānī رحمه الله juga menyatakan:
"لأن الغرر في الأعيان أكثر وأشد خطراً منه في المنافع، إذ المنافع لا تدوم، والأعيان تقتضي الملك والاستدامة"
"Karena gharar dalam barang lebih banyak dan lebih berbahaya dibandingkan gharar dalam manfaat, sebab manfaat tidak berlangsung lama, sementara barang mengandung kepemilikan dan keberlangsungan." (Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ, 5/144)
Contoh-contoh yang disebutkan ulama untuk membolehkan akad jasa meskipun ada unsur gharar:
- Jasa berburu: Tidak pasti hasilnya, namun dibolehkan (al-Mughnī, 5/7)
- Jasa pengobatan: Hasil kesembuhan tidak dijamin, namun jasa dibolehkan (Badā’iʿ al-Ṣanā’iʿ, 4/189)
- Jasa penggalian sumur: Air belum tentu ditemukan, namun tetap boleh (al-Mughnī, 5/7)
- Jasa penunjuk jalan: Hasilnya belum tentu aman, namun jasa tersebut dibolehkan
Kesimpulannya, gharar dalam jasa diberi kelonggaran selama tidak sampai pada tingkat gharar fāḥish yang menipu atau sangat spekulatif. Perbedaan ini menjadi penting dalam menilai akad jasa perjalanan seperti haji furoda.
Ibn Qudāmah menyebutkan dalam al-Mughnī (5/404):
"ولو استأجر رجلاً ليحفر له بئراً في موضع يرجو أن يجد فيه الماء، جاز، وإن لم يجده، لأنه يعمل بعينه، وقد يعذر في فوات الماء"
"Jika seseorang menyewa orang untuk menggali sumur di tempat yang diperkirakan ada air, maka itu boleh, meskipun ternyata tidak ada airnya. Karena yang dibayar adalah jasanya, dan kegagalan mendapatkan air bukan karena penipuan."
Al-Nawawī dalam al-Majmūʿ (9/304):
"ويصح أن يستأجره ليعلم ولده القرآن، أو الكتابة، أو صنعة، وإن لم يذكر قدر الزمان، لأنه ينصرف إلى العرف"
"Boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan anaknya al-Qur'an atau menulis atau suatu keahlian, meskipun waktu pengajarannya tidak disebutkan secara rinci, karena kembali kepada urf (keumuman)."
Al-Mardāwī dalam al-Inṣāf (6/19):
"تصح إجارة الخياط على خياطة ثوب معين ولو لم يذكر مدة العمل، ما دام العمل واضحًا والمدة تُفهم من العرف"
"Sah menyewa penjahit untuk menjahit baju tertentu meskipun tidak disebutkan durasi kerjanya, selama pekerjaan tersebut jelas dan lama kerjanya dapat dipahami dari kebiasaan umum."
Kesimpulan:
- Dalam akad barang (baiʿ), tinjauan gharar lebih berat dan dapat membatalkan akad.
- Dalam akad jasa (ijārah), tinjauan gharar lebih ringan (yasīr) tidak membatalkan akad selama kejelasan manfaat dan harga tetap terpenuhi.
Paket perjalanan haji ataupun umroh, akad jual beli barang atau akad Jasa??
Seluruh paket perjalanan baik yang bersifat wisata maupun tujuan tertentu seperti perjalanan dinas, studi banding dan termasuk didalamnya adalah haji dan umroh, termasuk haji furoda ataupun mujamalah, adalah menawarkan jasa pelayanan perjalanan dengan meliputi pelayanan fasilitas didalamnya.
Akad Paket Haji Furoda: Jasa atau Barang?
Akad penyelenggaraan haji furoda secara hakikat adalah akad jasa (ijārah), bukan jual beli barang (bai'). Yang dijanjikan bukanlah barang, tetapi pelayanan mulai dari pengurusan visa, akomodasi, transportasi, pembimbingan ibadah, hingga kepulangan.
Contoh Semisal di Zaman Klasik: Ulama klasik membahas kasus-kasus jasa dengan ketidakpastian hasil, namun tetap dibolehkan selama objek jasa jelas dan ada usaha:
- Menyewa seseorang untuk mengobati pasien: hasil tidak dijamin sembuh, tetapi tetap sah karena yang dibayar adalah usaha dan keahlian (al-Mardāwī, al-Inṣāf, 6/65).
- Menyewa nelayan untuk menangkap ikan dengan ketentuan jenis dan waktu tertentu, walaupun hasil tidak pasti (al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 13/219):
"وَإِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَصِيدَ لَهُ سَمَكًا فِي بَحْرٍ مَعْلُومٍ، جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ الْحُصُولَ، لِأَنَّهُ يَسْتَأْجِرُ جُهْدَهُ وَخِبْرَتَهُ فِي الصَّيْدِ"
"Apabila seseorang menyewa orang lain untuk menangkapkan ikan di laut tertentu, maka hukumnya boleh, meskipun tidak dijamin hasilnya. Karena yang disewa adalah upaya dan keahliannya dalam menangkap ikan." (al-Mabsūṭ, 13/219)
Kesimpulan: Oleh karena itu, akad paket haji furoda/mujamalah sebagai jasa perjalanan (bukan jual beli barang) harus dilihat dalam perspektif muamalah jasa, bukan muamalah jual beli barang.
Jika penyelenggara menjelaskan transparansi layanan, proses, dan risiko, serta adanya jaminan pengembalian dana, maka gharar di dalamnya termasuk ringan (yasīr), dan Gharar yang ringan (Yasir) tidak membatalkan akad menurut mayoritas ulama.
Tentunya mungkin ada yang berpendapat bahwa itu adalah gharar fahisy (nyata dan berat), maka kembali dari perbedaan perspektif dari cara pandang terhadap salah satu objek.
Dengan pemahaman ini, maka tidak tepat mengharamkan akad haji furoda secara mutlak hanya karena kemungkinan visa ditolak, selama penyelenggara menjelaskan kemungkinan tersebut secara terbuka dan memberikan jaminan atau kompensasi apabila tidak berangkat. Wallāhu aʿlam.
Hukum Asal Muamalah dan Kaidah Fikih Terkait Gharar
Setelah membahas karakteristik gharar dalam akad jasa serta pendapat para ulama mengenai perbedaan antara jual beli barang dan jasa, maka penting untuk mengaitkannya dengan hukum asal muamalah dan kaidah-kaidah fikih yang relevan.
Hukum Asal dalam Muamalah Adalah Boleh
Kaedah utama dalam fikih menyatakan:
الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."
Kaedah ini dipegang oleh mayoritas fuqaha, seperti disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim:
Ibn Taymiyyah رحمه الله berkata:
"الأصل في العقود والمعاملات الصحة وعدم التحريم إلا ما دل الدليل على تحريمه"
"Hukum asal dalam akad dan muamalah adalah sah dan tidak haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya." (Majmūʿ al-Fatāwā, 29/3)
Ibn al-Qayyim رحمه الله menyatakan:
"الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل"
"Syariat itu dibangun dan didasarkan pada hikmah dan kemaslahatan hamba—baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Seluruh syariat itu adalah keadilan, seluruhnya adalah rahmat, dan seluruhnya adalah maslahat. Maka setiap perkara yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kekerasan, dari maslahat menuju mafsadat, maka itu bukan bagian dari syariat—meskipun dimasukkan ke dalamnya dengan takwil." (Iʿlām al-Muwaqqiʿīn, 3/3)
Dengan demikian, setiap bentuk akad yang tidak terdapat larangan eksplisit dalam syariat, maka termasuk dalam perkara yang boleh dilakukan, termasuk jasa penyelenggaraan haji furoda atau perjalanan wisata.
الأصل في الأشياء الإباحة
“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.”
(Kaidah ushul yang disepakati mayoritas ulama: Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Suyuthi, al-Shawkani, dan lain-lain)
Hukum asal ini tidak boleh diubah kecuali dengan dalil yang mu’tabar dan qath’ī, atau dengan ẓannī yang jelas dan kuat secara tarjīḥ (kuat karena didukung oleh dalil, qiyās, atau ijma’).
Pendapat Ulama Tentang Pengaruh Dalil Ẓannī terhadap Hukum Asal
Imam al-Syathibi mengatakan:
"الأصل في الأدلة أن لا يخرج بها عن مقتضى الأصل إلا بدليل واضح لا معارض له، فإذا تعارضت الأدلة فالرجوع إلى الأصل من القواعد المقررة."
“Hukum asal tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan dalil yang jelas dan tidak memiliki pertentangan. Jika ada pertentangan, maka kembali kepada hukum asal adalah kaidah yang ditetapkan.” (al-Muwāfaqāt, 4/279)
Imam al-Sarkhasi (ulama Hanafiyah) berkata:
"إذا كان الأصل الإباحة، فلا يزول إلا بنص صحيح صريح يدل على التحريم"
“Jika hukum asal suatu perkara adalah boleh, maka tidak berubah kecuali dengan nash yang shahih dan sharih (tegas) yang menunjukkan keharamannya.” (al-Mabsūṭ, 30/13)
Implikasi
- Dalil ẓannī tidak cukup untuk mengharamkan suatu akad muamalah yang hukum asalnya adalah boleh, kecuali jika telah memenuhi syarat tarjih dan kuatnya indikasi larangan.
- Sebaliknya, jika dalil larangan berasal dari ijtihad atau ghalabah al-ẓann, maka tidak mengangkat/menghilangkan hukum asal kecuali dalam konteks iḥtiyāṭ (kehati-hatian), bukan sebagai pengharaman mutlak.
Kaidah terkait dengan wasilah untuk menyempurnakan kewajiban maka menjadi wajib.
Kaidah ini berbunyi:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
"Apa yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia wajib pula."
Imam al-Shuyūṭī menyebutkan kaidah ini sebagai prinsip dasar dalam ushul fikih:
"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"
(al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir, hlm. 60)
Imam al-Subkī رحمه الله berkata:
"الوسيلة إلى الواجب واجبة، فإنها إن لم تكن واجبة أفضى إلى تفويت الواجب، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام"
"Wasilah menuju kewajiban itu wajib. Jika tidak dianggap wajib, maka akan menyebabkan hilangnya kewajiban. Sesuatu yang mengantarkan pada yang haram, maka ia pun haram."
(al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir, al-Subkī, 1/47)
Imam al-Qarāfī juga menegaskan:
"الوسيلة إلى الواجب واجبة"
"Sarana yang mengantarkan kepada kewajiban adalah wajib.” (al-Furūq, 1/171)
Imam al-Shāṭibī رحمه الله menyatakan prinsip serupa dalam al-Muwāfaqāt:
"المقدمات التي لا يتوصل إلى أداء الواجب إلا بها لها حكم الواجب"
"Segala pengantar (muqaddimāt) yang tidak dapat dicapai pelaksanaan kewajiban tanpanya, maka ia mendapatkan hukum wajib." (al-Muwāfaqāt, 1/61)
Kaidah ini memiliki implikasi dan aplikasi penting dalam konteks istiṭhāʿah (kemampuan) dalam ibadah haji.
Jika seseorang tidak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah haji kecuali dengan jalan mendaftar lebih awal, atau menggunakan jalur tertentu seperti haji khusus atau furoda karena kondisi antrian reguler yang sangat lama, maka upaya-upaya itu bisa menjadi bagian dari syarat istithāʿah.
Haji sebagai Kewajiban Sekali Seumur Hidup dan Segera Jika Mampu
Nabi ﷺ bersabda:
"يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم"
"Wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian." Maka seorang laki-laki bertanya: "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Beliau diam. Hingga laki-laki itu mengulanginya tiga kali. Maka Nabi ﷺ bersabda: "Kalau aku katakan 'ya', niscaya akan menjadi wajib, dan kalian tidak akan mampu." (HR. Muslim, no. 1337)
Dari hadits ini, para ulama menyatakan bahwa haji wajib segera ditunaikan jika telah mampu (istithāʿah).
Syaikh al-Albānī رحمه الله menyatakan:
"من قدر على الحج ولم يحج فهو آثم عند الله، لأنه ترك واجبًا شرعيًا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل"
"Barangsiapa yang mampu menunaikan haji namun tidak melakukannya, maka ia berdosa di sisi Allah, karena ia telah meninggalkan kewajiban syar’i. Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: 'Barangsiapa yang berniat (ingin) berhaji, hendaklah ia menyegerakannya.'" (al-Silsilah al-Ṣaḥīḥah, no. 990)
Begitu pula Syaikh Ibn Bāz رحمه الله:
"يجب الحج على الفور لمن استطاع السبيل إليه، ولا يجوز تأخيره، ومن أخره فهو آثم"
"Haji wajib ditunaikan segera bagi siapa saja yang telah mampu menempuh jalannya. Tidak boleh ditunda, dan barangsiapa yang menundanya maka ia berdosa." (Fatāwā Nūr ʿala al-Darb, Ibn Bāz)
Istithāʿah Kontemporer dan Pendaftaran Haji
Istithāʿah tidak hanya dipahami sebagai kemampuan fisik dan finansial, tetapi juga akses administratif dan jalur keberangkatan yang riil. Di Indonesia, realita bahwa kuota terbatas dan masa tunggu reguler mencapai 20–40 tahun telah memunculkan diskusi fiqih kontemporer: apakah mendaftar reguler sudah cukup sebagai bentuk pelaksanaan istithāʿah?
Syaikh Muhammad Ṣāliḥ al-Munajjid حفظه الله berkata:
"فمن كان قادراً على الحج وجب عليه المبادرة بالتسجيل في الحملة الرسمية، وعدم التأخير بحجة أن الموعد بعيد، فالمهم هو السعي لأداء هذا الركن."
"Barang siapa yang telah mampu berhaji, maka wajib baginya segera mendaftar ke travel haji resmi dan tidak menundanya dengan alasan jadwalnya masih jauh. Yang terpenting adalah berusaha menunaikan rukun ini." (Shurūṭ al-Ḥajj wa al-ʿUmrah, hlm. 71, Dār al-Muslim)
Fatwa Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī juga menyatakan:
"إذا تأخر موعد الحصة الرسمية بحيث يخشى من عدم تمكن المكلف من أداء الفريضة، فإن اللجوء إلى البدائل الرسمية الأخرى التي تقصر المدة واجب على المستطيع."
"Apabila jadwal haji dari kuota resmi tertunda sampai dikhawatirkan orang yang wajib berhaji tidak dapat menunaikan ibadah tersebut, maka wajib bagi orang yang mampu untuk mengambil alternatif resmi lain yang mempercepat waktu pelaksanaan haji." (Muʿtamar Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī, 2006)
Bila seseorang hanya mampu mendaftar haji reguler, maka wajib baginya segera mendaftar sebagai bentuk usaha menunaikan istithāʿah. Dan jika memiliki kemampuan lebih untuk mendaftar haji yang lebih cepat, maka wajib baginya untuk mencari jalan yang lebih cepat jika mampu.
Jika belum memiliki dana untuk pelunasan, maka tidak berdosa, namun tetap perlu berniat serius dan berusaha menyempurnakan kemampuan.
Dasar Pendapat yang Mengharamkan Haji Furoda dan Pendapat Lain Yang Berbeda Silakan Klik Disini